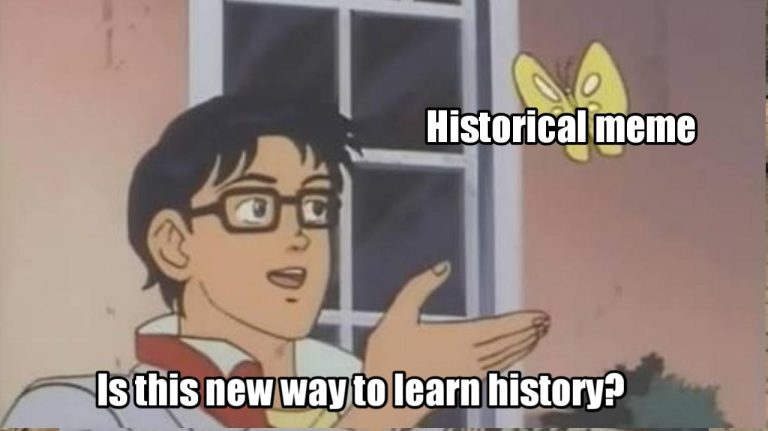Pada 5 Februari 2021 lalu, seorang teman, yang bekerja sebagai guru di SMA alma mater saya dulu, menghubungi grup WhatsApp angkatan. Ia meminta saya untuk datang ke acara hari ulang tahun (HUT) sekolah.
Kebetulan, rumah saya dekat dengan sekolah tempat ia bekerja, dan saya putuskan untuk mengunjungi teman saya tersebut. Di sana, kami berbincang mengenai masa-masa sekolah dulu di ruang guru. Ia duduk di meja kerjanya, sementara saya duduk di meja sebelahnya.
Di dekat meja tempat saya duduk, terdapat meja seorang guru sejarah yang pernah mengajari saya ketika saya masih belajar di sana. Di meja tersebut, terdapat tumpukan buku ajar sejarah untuk SMA berbagai kelas dari berbagai satuan kurikulum. Dekat buku tersebut, terdapat beberapa tumpukan kertas tugas para siswa.
Saya membaca beberapa tulisan siswa yang termuat di kertas-kertas tersebut. Sontak, saya terkejut, ketika saya menemukan tugas mengenai sejarah NATO dan SEATO, yang memiliki jawaban mirip-mirip antara satu dan lainnya. Setelah saya bandingkan dengan salah satu buku ajar sejarah Indonesia untuk kelas XII, saya menemukan jawaban siswa hampir persis dengan keterangan dalam buku ajar tersebut.
Apa yang dapat kita maknai dari kisah di atas? Sederhana, yakni di tingkat sekolah, pemahaman siswa akan sejarah masih bersifat didaktis alias mengikuti buku ajar dan keterangan guru yang mengajar di kelas. Siswa masih belum tergerak untuk melihat sejarah lebih jauh, terutama di luar buku ajar. Guru juga sepertinya sulit untuk mengembangkan kemampuan heuristik mereka, mencari referensi yang berbeda dan khusus di luar buku panduan.
Melihat kondisi ini, saya teringat dengan sebuah tulisan yang pernah saya baca ketika kuliah dulu. Tulisan tersebut mengatakan bahwa cara siswa belajar sejarah di Indonesia, terutama di bangku sekolah, masih bersifat menekankan pemberdayaan rasa nasionalisme dan kebangsaan siswa. Mereka diajak belajar sejarah bukan untuk memahami masa lalu secara kompleks dan objektif, tetapi hanya untuk menghayati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela Indonesia.
Pendekatan seperti ini, untuk siswa sekolah dasar (SD), mungkin masih cocok, sekadar untuk memantik minat mereka akan sejarah. Namun, untuk tingkat SMP dan SMA/SMK, setidak-tidaknya sejarah yang lebih kritis perlu disajikan. Terutama pada jenjang SMA/SMK, mereka telah mengenal kisah-kisah sejarah di luar pemahaman umum dewasa ini melalui internet dan budaya populer, dan oleh sebab itu, sudah sepantasnya mereka dikenalkan sejarah yang lebih spekulatif dan menekankan unsur subjektivitas.
Disayangkan, meski Indonesia telah lama terbebas dari belenggu kolonisasi dan menjadi negara-bangsa yang merdeka, cara negara mengenalkan sejarah kepada pelajar Indonesia masih bersifat kaku, selayaknya dogma-dogma dalam ajaran agama. Entah kapan kita akan melihat reformasi dalam hal ini, kita hanya bisa menunggu geliat dari pemerintah dan pemangku kebijakan.